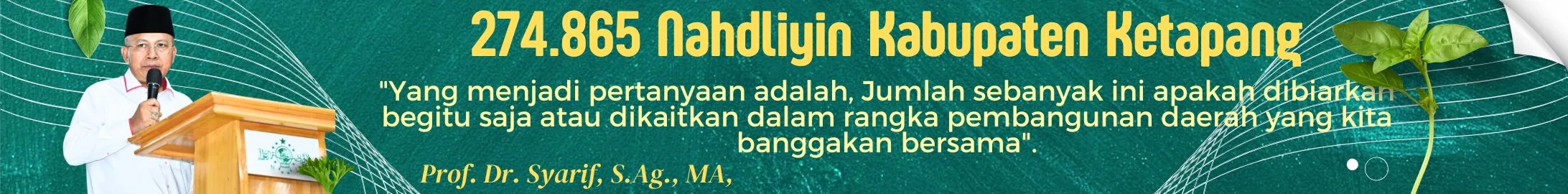Merintis Pesantren Tanpa Donasi Terbuka: Tantangan Kiai Muda
Merintis pembangunan pesantren tidak hanya membutuhkan keilmuan agama seorang pengasuh, tetapi juga dana yang tidak sedikit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, masjid atau setidaknya musala dan asrama merupakan bagian dari arkanul ma’ahid, yaitu rukun utama pesantren. Untuk mewujudkan kedua rukun ini saja sudah membutuhkan dana yang besar, belum lagi biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan kelas dan fasilitas lainnya.
Apakah mungkin membangun dan mengembangkan pesantren tanpa membuka donasi terbuka? Jika pertanyaannya adalah apakah mungkin, jawabannya tentu saja mungkin. Namun, apakah hal ini bisa diterapkan oleh semua orang yang ingin membangun dan mengembangkan pesantren? Jawabannya tentu tidak. Pertanyaan ini terpicu dari sebuah postingan di Facebook.
Ahmad Karomi, seorang alumni pesantren yang telah belajar lebih dari 10 tahun dan melanjutkan pendidikan formal hingga jenjang S3, memberikan semacam tantangan melalui postingannya. Tantangan ini ditujukan kepada kiai-kiai muda yang sedang merintis pesantren.
Jika pesantren dibangun dan nantinya pengembangannya akan dilanjutkan oleh keturunan kiai, beranikah kiai-kiai muda itu merintis dan mengembangkan pesantren tanpa melalui donasi terbuka? Secara tidak langsung Ahmad Karomi ingin menegaskan, rasanya tidak etis jika mereka mengandalkan donasi terbuka, padahal pesantren tersebut pada dasarnya bukan lembaga publik milik masyarakat.
Tulisan ini akan membahas alasan di balik praktik donasi terbuka di pesantren dan bagaimana pesantren dapat belajar dari contoh pesantren yang berkembang secara mandiri. Sebagai Pengingat Donasi terbuka adalah salah satu metode penggalangan dana yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Metode ini memberikan manfaat besar, terutama bagi pesantren yang baru dirintis dan belum memiliki banyak sumber daya.
Donasi terbuka juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pesantren. Meski ada hal positif, secara jujur, tantangan yang disampaikan dalam postingan di Facebook di atas merupakan pengingat bagi kiai-kiai muda yang sedang merintis pesantren, terutama ketika mereka lebih mengutamakan donasi terbuka untuk mendukung pengembangan pesantren.
Cara seperti ini menunjukkan bahwa pesantren belum mandiri secara finansial, sehingga masih bergantung pada bantuan dari pihak lain untuk berkembang. Namun dibalik kritik ini, terdapat alasan yang mendasari mengapa banyak pesantren akhirnya mengandalkan donasi terbuka. Memang tidak mudah memastikan apakah mayoritas pesantren berdiri dan berkembang melalui donasi terbuka. Sama sulitnya untuk mengetahui pesantren mana yang berhasil berkembang dengan prinsip kemandirian.
Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa kebanyakan kiai muda yang merintis pesantren biasanya terdorong untuk mendirikan pesantren setelah menyelesaikan studi agama di pesantren selama bertahun-tahun. Bahkan, banyak di antara mereka yang melanjutkan pendidikan formal setelah lulus dari pesantren. Setelah merasa cukup dengan ilmu yang diperoleh, mereka pulang ke kampung halaman dengan niat berkhidmah di masyarakat dengan mendirikan pesantren.
Pesantren menjadi sarana bagi mereka untuk mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari. Inilah jalur umum yang biasanya ditempuh oleh kiai-kiai muda dalam mendirikan dan mengembangkan pesantren. Namun, jika kita melihat pola ini, tidak banyak kiai muda yang memiliki modal finansial kuat sebagai modal awal untuk mendirikan pesantren. Modal terbesar yang mereka miliki adalah ilmu agama, yang memang menjadi salah satu syarat utama untuk mendirikan pesantren.
Melalui pesantren, mereka ingin mengabdikan diri dengan menyebarkan ilmu agama yang telah mereka pelajari, baik di pesantren maupun di pendidikan formal. Ketika mereka mendirikan pesantren, namun tidak memiliki modal finansial yang besar, donasi terbuka menjadi salah satu cara “termudah” untuk memastikan pesantren tetap beroperasi, bahkan berkembang.
Mencapai kondisi ideal bagi kiai muda yang ingin mendirikan pesantren tentu bukan hal mudah. Kondisi idealnya adalah memiliki ilmu agama yang mumpuni serta modal finansial yang kuat sebelum mendirikan pesantren. Namun, berapa banyak kiai muda yang memenuhi kriteria ideal ini? Tanpa perlu melakukan survei, kita bisa menyadari bahwa jumlahnya sangat sedikit. Mengapa demikian? Saat kiai muda masih menuntut ilmu di pesantren, sebagian besar dari mereka tidak belajar kewirausahaan, apalagi mempraktikkannya.
Fokus mereka adalah belajar ilmu agama, yang memang menjadi tugas utama di pesantren. Selain itu, faktanya tidak banyak pesantren yang mengajarkan kewirausahaan. Karena itu, selain minim pengetahuan teori kewirausahaan, para santri juga tidak memiliki pengalaman dalam membangun bisnis setelah selesai belajar di pesantren.
Belajar dari Pengalaman Meski kondisi ideal ini tampak sulit dicapai, bukan berarti tidak ada pesantren yang mampu berdiri dan berkembang dengan prinsip kemandirian. Salah satu contohnya adalah Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati di Jepara, Jawa Tengah. KH. Taufiqul Hakim memulai Pesantren Amtsilati pada tahun 1995, setelah menyelesaikan studinya di Perguruan Islam Mathali’ul Falah, Pati, Jawa Tengah pada tahun yang sama. Beliau mengawali khidmahnya dengan mengajar anak-anak di musala. Pelajaran yang diajarkan meliputi tajwid, Aqidatul Awam, Aafinatun Najah, dan bahasa Inggris.
Ketika mengajar pelajaran nahwu dengan menggunakan kitab Jurumiyah, Kiai Taufiq menyadari bahwa anak-anak mengalami kesulitan dalam memahaminya. Melihat situasi ini, beliau melakukan istighatsah serta khataman doa khowajikan. Selanjutnya, beliau terinspirasi oleh metode membaca Al-Qur’an Qiro’ati, yang kemudian memicu Kiai Taufiq menyusun metode membaca kitab kuning yang kemudian diberi nama Amtsilati (Sang Pembaharu Pendidikan Pesantren, 2019). Amtsilati, yang berarti “contoh-contoh dari saya”, merupakan ringkasan dari kitab Alfiyah Ibnu Malik.
Metode ini memperpendek lebih dari seribu bait Alfiyah menjadi sekitar 100 bait. Selain jumlah bait yang ringkas, metode ini juga diperkaya dengan contoh-contoh dari Al-Qur’an dan dimulai dari materi-materi yang mudah, seperti huruf jer (kata depan), isim dhomir (kata ganti), dan isim isyarah (kata tunjuk). Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan akan kitab Amtsilati juga meningkat. Awalnya hanya dicetak secara fotokopi, Kiai Taufiq kemudian merintis mendirikan penerbit dan percetakan sendiri. Selain mencetak dan mendistribusikan kitab Amtsilati, penerbit ini juga mendistribusikan karya-karya Kiai Taufiq lainnya yang jumlahnya lebih dari 200 judul buku.
Selain berfungsi mendistribusikan karya Kiai Taufiq, penerbit dan percetakan ternyata berkembang menjadi lini usaha pesantren yang turut melahirkan usaha-usaha lain seperti minimarket, toko bangunan, dan produksi air mineral. Usaha bisnis inilah yang ikut membantu menopang kemandirian pesantren, yang kini memiliki lebih dari 3.000 santri. Dalam kurung waktu tiga tahun terakhir ini, saya sering berkunjung ke Pesantren Amtsilati untuk menengok putra yang nyantri di sana. Pesantren ini seperti tidak pernah berhenti melakukan pengembangan pesantren, baik dari perluasan lahan, penambahan fasilitas gedung, hingga inovasi pembelajaran. Salah satu inovasi pembelajaran di pesantren berlaku bagi anak-anak Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mengikuti program tahfidzul qur’an. Program ini tidak diawali dengan menghafal al-Qur’an.
Sebaliknya, anak-anak terlebih dahulu mempelajari kitab kuning melalui metode Amtsilati. Selah lulus mengikuti metode ini, mereka diharapkan dapat lebih mudah menghafal al-Qur’an karena sudah memiliki dasar yang baik dalam pelajaran nahwu-sharaf. Keberhasilan Kiai Taufiq dalam merintis Pesantren Amtsilati dapat menjadi inspirasi bagi alumni pesantren yang ingin mendirikan pesantren secara mandiri. Dari pengalaman beliau, kita belajar bahwa tanpa pengetahuan dan praktik bisnis, seorang alumni pesantren ternyata dapat membangun pesantren secara mandiri dengan modal keberanian, ilmu, dan tekad yang kuat.
nuOnline: Faishol Adib, alumnus Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta & Chinese Language Enthusiast